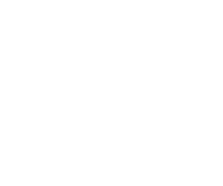MENCERNA JIWA KORSA
 KOPASUS
KOPASUS
|
Pilihan Redaksi
|
Lider : Jakarta -
Peristiwa Cebo ngan, penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang teletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta), di bulan Maret tahun 2013, hingga kini bagai ‘sebuah kitab keramat’ bagi pasukan elit Angkatan Darat bernama Komado Pasukan Khusus (Kopassus). Pasalnya, dari peristiwa berdarah itu, esprit de corps—istilah yang dipakai Napolen Bonaparte di tahun 1870-an, atau jiwa korsa di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, mendapatkan momentumnya untuk ditemu kan atau dipahami kembali (revisited).
Adalah aksi 11 prajurit Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, Jawa Tengah yang menyerbu LP Cebongan dan menghabisi empat gembong preman (yang ditahan di lapas itu) yang telah membunuh teman satu ke satuan mereka Sersan Kepala Santoso. Jiwa korsa—rasa senasib, sependeritaan- yang terbangun dan terpatri dalam diri prajurit melalui latihan dan tempaan yang keras sebagai anggota Komando Pasukan Khusus, menyatakan diri secara ’innocent’. Penyelidikan yang dilakukan sesudah kejadian itu mengesahkan bahwa kasus Cebongan adalah aksi balas dendam murni yang melibatkan anggota masyarakat sipil dan anggota pasukan khusus, Kopassus. Yang membuatnya ‘sexy’ adalah locus, tempat kejadian perkara, yakni sebuah penjara yang dijaga ketat pihak Kepolisian.
Dan, berikutnya, adalah korban yang dihabisi anggota Kopassus yang adalah biang kerok yang membuat onar dan meresah kan masyarakat di Yogyakarta. Di persimpangan ini kita menemukan narasi yang saling berbelit. Berbagai suara bertabrakan, antara mengecam dan memuji tindakan berani anggota Kopassus hampir di saat yang sama.
Sementara pelaku kasus Cebongan sudah mengaku salah dan diproses hokum sebagaimana mestinya, tak sedikit juga warga masyarakat Yogyakarta yang bersukacita atas tindakan berani anggota Kopassus yang membebas kan mereka dari cengkraman preman yang meresahkan dan menghantui kehidupan sosial mereka. Ingatan kolektif masyarakat tentu tertuju pada spanduk-spanduk dukungan untuk anggota Kopassus yang tersebar dari Yogyakarta hingga Solo kala itu. Secara linear Danjen Kopassus Mayor Jenderal Iwan Setiawan mengatakan kasus Cebongan lebih bermakna pesan moral untuk tidak bermain-main dengan Kopassus karena Kopassus dapat berbuat apa saja jika korps baret merah dilecehkan.’
“Dia (Santoso) sudah mengaku Kopassus, tetapi tetap diinjak dan diseret-seret seperti binatang. Anggota yang lain merasa tersinggung dan marah karena merasa korpsnya dilecehkan,” kata Iwan Setiawan.
Ia menambahkan,” toh anggota sudah mengaku bersalah dan sudah diproses hukum. Tetapi harus juga dilihat reaksi masyarakat yang merasa terbebas kan dari para pembuat onar itu.”
Betapapun, pengamat militer, Andi Widjajanto menilai, harus ada rekonstruksi pemahaman jiwa korsa antar prajurit sehingga tidak bertabrakan dengan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Menurut
nya, jiwa korsa tidak lagi bisa menjadi alasan tindakan melawan hukum. Emosi Berlebih Esprit de corps atau jiwa korsa menjadi begitu sentral dalam sebuah organisasi militer, apalagi pasukan khusus yang berfungsi sebagai senjata pamungkas. Airman handbook yang diterbitkan Angkatan Udara Amerika Serikat menyebut esprit de corps sebagai a magic substance that brings a military organization to life”—sesuatu yang tidak kelihatan tetapi menggerakan dari dalam.
Dalam ungkapan yang lain, mantan pengamat militer Dr. Salim Said secara singkat berkomentar, semakin tinggi resiko dan gambaran tentang resiko yang dihadapi, semakin tinggi pula esprit de corps itu di lingkungan tentara. Umumnya, jiwa korsa terkait erat dengan semangat bertempur untuk mencapai yang impossible. Literatur mengenai jiwa korsa menyebutkan selain sebagai roh yang menggerakan kesatuan, jiwa korsa bertum puh pada moral individu dalam melihat timnya serta tujuan bersama yang ingin dicapai. Dan menjadi jelas bahwa pasukan elit yang dilatih dan di doktrin untuk ‘lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga”, pada tempat pertama, memiliki jiwa korsa yang juga istimewa, jauh diatas kesatuan regular lainnya—karena keper cayaan bahwa mereka adalah anggota dari kesatuan yang terbaik di dunia. Tetapi, nampaknya, disitulah pula tantangan itu muncul. Pengamat intelijen Prayitno Ramelan mencatat sederet kasus yang dilakukan tentara— disamping kasus Cebongan— yang terjadi di sepanjang tahun 2013 dan menyimpulkan ada emosi yang tidak terkendali diantara prajurit TNI.

Analisanya dibuat dengan mengacu pada statement para petinggi militer waktu itu seperti mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriarto no Sutarto, mantan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan mantan Direktur Hukum Direktorat Jenderal Pertahanan M. Fachruddin. Mantan penasehat Menteri Pertahanan era Matori Abdul Djalil itu memberikan catatan khusus bahwa terdapat aksi-aksi yang dilakukan oknum militer yang memang tercover oleh esprit de corps, adanya pemahaman yang salah tentang jiwa korsa, khususnya di kalangan prajurit muda, serta disiplin (tertib hukum) yang rendah di kalangan tentara.
Secara khusus Prayitno Ramelan meminta kehati-hatian para petinggi militer dalam menggunakan dalih esprit de corps untuk membela pasukan nya karena tanpa pemahamanyang mendalam dikhawatirkan anggota pasukan akan kembali melakukan tindakan kekerasan kelompok terhadap siapapun yang dianggapnya perlu dibalas dengan tindak kekerasan. Dalam sebuah bincang- bincang dengan Lider, Danjen Kopassus Mayor Jenderal Iwan Setiawan mengatakan Jam Komando di Kopassus mempunyai arti yang strategis dalam membangun jiwa korsa yang positip di kalangan pra- jurit. Komandan satuan harus sering mendatangi anggotanya sehingga dapat mengetahui gejolak dibawah untuk dian tisipasi. Komandan juga harus memberikan pengertian bahwa jiwa korsa harus dipakai dalam arti positif, bukan yang justru merusak citra korps karena jiwa korsa dimaknai bagai kewajiban membela anggota apapun alasannya. “Kita tidak bisa terbawa emosi dan asal membela anggota begitu saja. Kita harus cek, siapa yang salah. Kalau anggota kita yang salah, ya, tetap salah,”katanya.

Berpikir Kedepan Peristiwa Cebongan sudah hampir satu dekade berlalu, dan anggota Kopassus pelaku penembakan sudah pulamenerima hukumannya. Tetapi ia bagai sebuah buku terbuka yang akan terus dibaca, diulas, dipahami dan disempurnakan. Hendardi, Ketua Setara Institut dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), pejuang kesetaraan dan keberagaman, memberikan catatanya secara profesional. Mengaku bahwa dialah salah satu diantara mereka yang keras berbicara tentang pelanggran HAM dalam kasus Cebongan, ia justru mengapresiasi sikap Lembaga Kopassus pasca peristiwa itu. “Sesuatu yang mengejutkan karena saya yang keras menuding Kopassus sebelum akhir nya kasus itu terkuak. Saya juga bicara keras tentang pelanggaran HAM oleh tentara tetapi justru dari situ saya mulai dekat dengan institusi tentara. Mereka (Kopassus, red) terbuka, mengundang saya pada rapat pimpinan dan mendengarkan masukan dari saya,” kata pemimpin SETARA institute itu. Menurut Hendardi, peristiwa Cebongan telah membuat tentara, Kopassus khusunya, berubah dari sebuah institusi tidak tersentuh dengan kebenaran dan tafsirnya sendiri atas apa yang dilakukan di masa Orde Baru.

Intinya, menurut Ketua Umum SETARA Institut itu, jiwa korsa harus dimaknai dalam kerangka perang menghadapi musuh dan tidak dibenar kan sikap main hakim sendiri, apapun alasannya, seperti kasus Cebongan itu. “Sebagai negara hukum, tidak dibenarkan instrument apapun untuk bertindak semaunya. Tindakan memberantas preman, misalnya, soal penegakan hukum, itu wewenang kepolisian, lepas dari bagaimana mereka penegakkannya,” kata Hendardi. “ Jiwa korsa tidak dapat diartikan sebagai solidaritas tanpa batas dan dengan itu dapat berbuat apa saja. Itu perpektif hukumnya.” Pendapat serupa diutarakan Prof. Arry Bainus, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Padjajaran, Bandung. Menurutnya, jiwa korsa harus dimaknai dalam konteksnya yaitu perang. Di saat damai, ketika semua anggota masyarakat harus tunduk pada tertib sipil, tunduk pada pemerintahan sipil, jiwa korsa justru cenderung bersifat negatif.

“Intinya, kalau berhadapan dengan sipil, jangan pakai kaca mata militer,” tandasnya. Era eksklusivisme tentara sudah berlalu dan setiap komandan, menurut Arry Bainus, harus berpikir dalam kerangka tertib hukum. Dalam situasi tidak perang, yang berlaku adalah supremasi sipil, dan menjadi bias ketika pelanggaran hokum oleh tentara dalam situasi non perang diberlakukan aturan militer. Dalam situasi damai, non perang, menurut peneliti soal militer ini, aturannya berlaku umum di seluruh dunia bahwa militer adalah warga sipil yang tidak dilindungi oleh hak is timewa atau oleh esprit de corps itu.
Inilah cara berpikir tentang jiwa korsa di era demokrasi. Dalam batas tertentu, espritde corps berarti loyalitas pada pimpinan, komandan, dan menjadi riskan ketika pimpinan memiliki agenda tersendiri,
kepentingan pribadi. Anggota Komisi I yang membawahi bidang pertahanan Hasbi Anshory mengatakan tentara harus patuh untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan yang lain, sesuai UU No.34 tahun 2004. “Akan sangat berbahaya jika ia tunduk pada kepentingan politik tertentu,” tandasnya.
Dalam perspektif ini Danjen Kopassus Mayjen Iwan Setiawan sudah sejak sangat dini, di hari pertama pelantikannya sebagai Komandan Kopassus yang ke-35, menekankan” Jaga Kehormatan Baret Merah.
Jangan sampai ternodai oleh kepentingan apapun. Kita harus loyal, tegak lurus kepada pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.” Dalam ekspesi yang beraneka, pesannya jelas: Kita membanggakan pasukan khusus kita yang profesional dan proporsional dalam menjaga kehormatannya dan kehormatanbangsanya. •